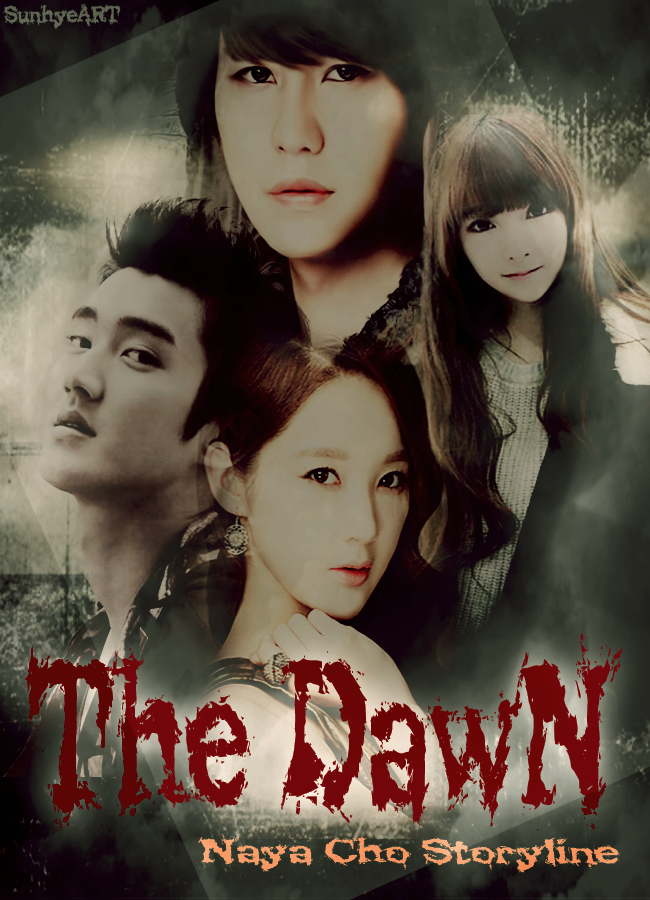Tujuh
Gone
“Cinta adalah alasan paling tepat untuk berbuat gila.”
***
Menyebalkan. Jika ditanya pendapatnya tentang pria brengsek bernama Shin Yonghwa itu, maka jawabannya sekarang hanya akan ada satu; MENYEBALKAN. Semua orang mungkin akan berpikir dia adalah pria tampan yang manis, bermata teduh, kalem, lumayan atletis, sopan, gentleman, dan blablabla yang bagus-bagus seolah-olah dia adalah titisan malaikat. Yah, memang terlihat seperti itu. Tidak ada yang tahu betapa sialannya pria itu. Tidak ada. Dan Synne merasa hampir mati karenanya saat ini.
Gadis itu, tidak memedulikan seberapa berantakannya dirinya atau kamarnya, ia hanya bisa fokus melotot pada layar ponsel yang tidak kunjung menyala. Pria itu tidak menghubunginya. Ia sudah mengirim pesan sebanyak tiga kali dengan mempertaruhkan seluruh harga diri dan kehormatannya, dan pria itu tidak membalasnya. Pria itu tidak membalas pesannya. Dengan kata yang lebih mudah, pria itu mengabaikannya. Parahnya, ini berlangsung sudah dua hari, dua hari penuh yang terasa seperti neraka karena tidak ada kabar dari pria sialan itu.
Synne mendesah kasar lagi. Antara ingin menangis dan berteriak mengumpat-umpat sampai suaranya habis, mengamuk sampai puas. Kenyataannya, yang bisa ia lakukan hanya berguling-guling di karpet dan membuat dirinya tampak tidak waras, seperti gelandangan yang berminggu-minggu tidak pernah membersihkan diri. Demi Tuhan ia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kabar dari pria itu—ia tidak pernah tahu bagaimana jadinya tanpa pria itu. Seolah… Shin Yonghwa adalah pengisi baterainya, yang membuatnya tidak akan berfungsi benar jika sehari tanpa mendengar kecerewetan pria itu menyuruhnya mandi, kuliah, dan segalanya. Mungkin, ia terlalu bergantung pada pria itu. Mungkin terlalu manja. Yang jelas, ia merasa sekarat sekarang.
“Dasar jelek! Awas saja kau nanti!” makinya pada ponsel. Jika saja ponsel memiliki otak sendiri, atau setidaknya memiliki perasaan, ia pasti sudah melarikan diri, atau meleleh karena terus-menerus disalahkan. Hei, ia hanyalah sebuah ponsel! Hanya sebuah barang yang kembarannya ada banyak sekali di dunia, tapi kenapa dia yang harus dimarahi??!
Lalu Synne melemparkannya, meringis, dan meraba rasa sesak di dadanya. Ia merasa… hancur berkeping.
Kenapa pria itu menghilang secara tiba-tiba, meninggalkannya, tanpa kepastian?
***
Perasaan seperti itu menyulitkan. Synne menemukan dirinya terbangun dini hari. Atau tepatnya… ia belum tidur. Ia sudah berusaha memejamkan mata namun tidak berhasil membuatnya mengantuk, hanya membuat matanya sakit karena dipaksakan terus menerus menutup.
Dan ia tidak berusaha lagi untuk tidur, tahu bahwa semua itu akan percuma. Laptopnya menyala, halaman yang harus ia ketik terbuka, siap untuk menyambung cerita novel yang seharusnya ia kerjakan. Tapi ia tidak melakukannya. Tidak bisa. Ia tidak melakukan apapun selain membiarkan laptopnya bernyanyi lagu-lagu ballad yang tidak ia dengarkan. Sekali lagi memeriksa ponselnya, dan mendesah lagi. Masih belum ada kabar.
Satu bulir kristal bening mengalir, disusul lelehan-lelehan berikutnya yang dengan segera berubah menjadi isak tak terkontrol.
Bodoh! Kau kemana saja, huh? Setidaknya… meski kau melupakanku, meski marah padaku, kau juga harus membiarkanku tahu bagaimana kabarmu. Apa kau baik-baik saja? Apa kau sudah makan? Apa sesuatu terjadi denganmu? Kau selalu menyuruhku makan yang banyak dan tepat waktu, tapi bagaimana bisa… bagaimana bisa kau tidak membiarkanku tahu kau sudah makan atau belum? Bagaimana dengan begitu aku bisa makan dengan baik?
Aku merindukanmu. Itu saja. Tapi tahukah kau bahwa merindukanmu rasanya semenyesakkan ini? Semenyakitkan ini? Mungkin aku egois, tapi aku merindukanmu saat memaksaku tidur lebih cepat dan mengucapkan selamat tidur. Aku merindukanmu yang membangunkanku pagi-pagi buta. Aku merindukanmu yang mengecek apakah aku sudah makan atau belum. Aku merindukanmu yang suka bertanya apakah aku sudah mandi atau belum. Aku merindukanmu yang penasaran dengan apapun yang kulakukan. Bahkan… aku merindukanmu yang mengomeliku jika aku malas mengerjakan tugas kuliah.
Kenapa kau menghilang tiba-tiba? Kenapa kau setega itu? Rasanya terlalu sakit, Brengsek!
Synne membekap mulutnya saat merasa tidak mampu menahan isakannya. Ia membesarkan volume lagu di laptopnya, berharap semua itu dapat menyembunyikan tangisnya yang parah. Tidak peduli ia sesak napas karena banyak menangis. Tidak peduli matanya akan bengkak yang mengerikan besok. Pria itu menghilang, hampir sama artinya dengan dunianya nyaris berakhir.
***
“Tidak, sudah hampir seminggu dia tidak datang bekerja. Tidak ada kabar. Kami juga khawatir dengannya.”
Jawaban yang Synne dapatkan ketika ia mencoba mengunjungi restoran tempat Yonghwa bekerja dan bertemu Tim, rekan kerjanya di The Duke. setelah pamit, gadis itu meneruskan langkah gontainya.
Ia sudah mencoba segalanya. Ia sudah memutuskan mengubur semua gengsinya yang segunung demi pria itu, hanya demi mengetahui keadaannya. Menelpon pria itu, mengirimi pesan, semua sudah ia lakukan beratus-ratus kali tanpa hasil. Ia juga sudah mendatangi flat pria itu, memencet belnya berkali-kali dan berdiri menunggu hingga larut malam, dan tetap tidak menemukan Yonghwa di manapun. Synne juga sudah menghubungi keluarganya di Korea, tidak ada berita soal kepulangan pria itu. Dan Synne, sudah sampai pada titik putus asanya sekarang.
Ketika ia berhenti melangkah, mendongak dan mengalihkan pandangan dari sepatunya kepada bangunan di depannya, ia tidak punya alasan kenapa ia bisa sampai di tempat itu. Ia hanya sampai di sana. Tanpa menyadari kakinya membawanya menyusuri Dowell Street dan berhenti di sebuah flat berlantai tiga. Pulang ke flat pria itu.
“Ini yang terakhir. Setelah ini… aku akan menyerah, Tuan Keparat. Aku tidak akan peduli lagi padamu!”
***
Dimitri menatap wujudnya di depan cermin. Sudah berhari-hari ia melakukannya. Tanpa bergerak, tanpa merasa perlu untuk bernapas atau melakukan sesuatu apapun yang membuatnya tampak hidup. Karena yah, ia memang bukan sesuatu yang hidup. Ia bergerak, lebih cepat dari yang bisa kau bayangkan, tapi ia tidak hidup. Ia hanya ada.
Tinggi sedang, rambut hitam yang tampak rapi, kulit putih khas Asia Timur, mata kecil yang teduh… ini bukan pertama kalinya, sebenarnya. Sebelumnya ia pernah menjadi seorang pria Korea dengan identitas Lee Jonghyun, seorang pelajar yang bekerja paruh waktu sebagai pelayan kafe. Dengan menyamar menjadi Lee Jonghyun yang malang—yang mati dengan jantung berlubang dan siapapun tidak tahu—ia pernah berhadapan dengan hal yang langka dalam hidupnya, saat pemakan jantung—Shimggun, sebutannya di Korea—yang lain bernama Kyuhyun mempertaruhkan eksistensinya demi seorang gadis Pemburu. Kisah cinta yang terlalu klasik hingga ingin muntah mendengarnya.
Tapi Dimitri tidak lagi bisa tersenyum sinis mengingat kisah itu. karena sekarang pria ini… pria yang ia pinjam identitasnya ini… melihat dirinya sendiri di cermin hanya membuat Dimitri merasa begitu… aneh. Pria itu sudah mati. Shin Yonghwa sudah mati. Dia sudah mati. Dimitri terus berusaha meyakinkan diri, tapi setiap kata dari pria itu tidak mampu menguap dari benaknya.
Flashback
Jalanan itu lengang. Bahkan bangunan-bangunan bata tinggi dan dingin di sekitarnya terasa seakan tidak ingin bicara, angin tidak berhembus sama sekali.
“Apa yang kau inginkan?” Pria itu bertanya, dan Dimitri dapat menangkap raut bingung serta curiga dari caranya menatap.
“Kau. Jantungmu. Dirimu… gadis itu.”
“Apa yang kau—“
“Gadismu, aku menginginkannya. Dia gadis yang kucintai selama ribuan tahun. Aku menunggunya ribuan tahun. Dan aku harus memilikinya sekarang. Aku tidak akan melepaskannya lagi.”
Normalnya, Dimitri tahu pria di depannya ini akan mengatakan dia gila. Tapi pria itu hanya menatapnya, seolah meneliti kebenaran yang Dimitri ucapkan dengan suara bergetar barusan. Sepanjang eksistensinya, ia tidak pernah mencoba mengungkapkan perasaannya pada siapapun. Mengungkapkannya ternyata membutuhkan energi sebesar itu.
“Synne? Yeon Hee-ku? Aku juga mencintainya, dan aku tidak memiliki rencana melepaskannya.”
Dimitri menemukan dirinya menggeram seketika mendengar ketegasan pria itu. Emosinya terbakar lebih cepat dari cara dia bergerak. Dalam waktu sepersekian detik ia sudah berdiri dekat sekali dengan pria itu, mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya. Matanya yang terbiasa biru keabuan sekarang berubah nyala menjadi merah darah, dengan titik-titik hitam membentuk pola acak.
“Aku akan memaksamu!”
Yonghwa terjatuh ke tanah di detik berikutnya. Muntah darah. Tangannya mencengkeram dadanya sebagai respon dari nyeri mendadak yang terasa menyengat. Rasanya panas. Ia disadarkan bahwa dadanya sudah terluka parah, ada luka sabet besar melintang di atas dada kirinya, dalam dan panjang. Dimitri membuatnya dengan mudah hanya dengan kukunya—atau apa yang tampak seperti kukunya yang tiba-tiba tumbuh memanjang.
“Lihat. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bahkan sempat berpikir bisa melindunginya?”
Dimitri menunduk, tangannya terjulur meraih dada Yonghwa. Jantung itu, jantung yang berdetak-detak di balik luka itu… ia sudah dapat merasakannya memanggil-manggil. Hangat dan nikmat. Namun Yonghwa mencengkeram lengannya, mencegahnya melakukan apapun yang ingin segera ia lakukan. Ia bisa saja menyentak cengkeram yang baginya terlalu lemah itu, tapi ia tidak segera melakukannya.
“Kau…,” Yonghwa terbatuk, noda darahnya terciprat ke kemeja yang dipakai Dimitri. “Kau bilang kau mencintainya, kan? Bisakah kau menjaganya?”
Pria berambut pirang flaxen itu hanya menatap kaku. “Ya, aku mencintainya. Dan aku akan melindunginya dari apapun.”
“Kau juga harus perhatian padanya. Dia sulit dibangunkan padahal ia ada kuliah pagi, kau harus membangunkannya sejak pagi-pagi sekali. Dia kadang lupa makan, lupa mandi, lupa membawa barang-barang penting yang ia perlukan, lupa menaruh segala sesuatu… kau harus mengingat semua untuknya dan mengingatkannya setiap waktu.” Yonghwa berhenti sejenak. Bernapas sekarang terasa menyakitkan, lukanya menganga terlalu lebar, darahnya terpompa keluar terlalu banyak, dan kepalanya mulai pusing.
“Kau juga harus memperhatikan pakaiannya, ia tidak pandai memilah baju yang sesuai, jangan sampai ia menjadi tertawaan orang-orang. Ia tidak pandai memasak dan hanya suka makan mie instant atau burger pinggir jalan. Sesekali kau harus memasak untuknya, mengisi kulkasnya dengan bahan makanan, dan mengingatkannya untuk tidak makan fastfood itu lagi, itu tidak sehat.
“Yeonnie… dia lahir hari Minggu, 27 desember, saat hari sedang hujan. Ia suka hujan, pohon, hutan, warna hijau dan cokelat, dia suka susu cokelat, es krim, permen kapas, tapi ia tidak begitu suka makanan manis, ia lebih suka yang gurih. Dia tidak suka memelihara hewan karena ia malas merawatnya, merawat dirinya sendiri saja tidak bisa. Dia tidak suka ikan laut karena baginya selalu amis, tapi dia suka lobster. Dia tidak suka makan berbagai daging kecuali ayam. Tolong… pastikan dia makan dengan baik.”
Dimitri tidak mengatakan apa-apa, sadar bahwa ia tidak akan bisa mengatakan apapun. Ternyata… banyak tentang gadis itu yang tidak ia ketahui. Ia tidak tahu harus senang atau apa mendengar semua informasi ini.
“Apa kau sudah selesai?”
“Terakhir bicara padanya… dia mengatakan dia membenciku. Tolong… jika kau bertemu dengannya katakan aku menyayanginya. Sangat.”
Pria berambut pirang yang berdiri anggun sekaligus kokoh itu berdecih pelan. Bukan dengan alasan benar-benar menghina, melainkan lebih kepada betapa ia tidak menyukai kenyataan bahwa ada pria lain yang memuji blackrosenya. Dan ketakutan bahwa pria lemah ini lebih mencintai gadis itu ketimbang apa yang sudah ia lakukan.
“Kau ingin mengambil jantungku?” tanya Yonghwa dalam bisikan parau.
“Ya.”
“Ambilah. Tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya.”
[End of flashback]
Dimitri masih tidak tahu, apakah benar yang sudah ia lakukan? Membunuh pria itu? Pria yang mencintai gadisnya sepenuh hati. Bisakah ia… menggantikan posisi pria itu?
Nyatanya sekarang ia tidak berani mengambil keputusan apa-apa. Ia tidak berani berada dalam jarak lebih dekat dari yang bisa ia bayangkan dengan gadis itu. Ia terbiasa melihatnya dari kejauhan, dan mungkin harus selalu seperti itu. Sekarang, situasinya berbeda. Ia bukan lagi Dimitri atau siapapun yang gadis itu tidak kenali, ia sekarang mengantongi seluruh identitas Shin Yonghwa, pria paling penting dalam hidup Synne, gadis itu. Fakta ini entah bagaimana membuatnya sesak, seandainya saja ia punya jantung.
Terdengar sekali lagi bunyi bel di pintu flat Yonghwa yang sekarang ia diami. Biasanya Dimitri tidak pernah memedulikannya, kali ini pun begitu, namun bel itu tidak berdentang lama, berganti dengan ketukan di pintu. Yah, ketukan di pintu kamarnya.
Merasa tidak percaya, Dimitri beranjak, ia tidak membutuhkan banyak usaha untuk selekasnya mencapai pintu itu, dan lebih tidak membutuhkan banyak usaha dalam upayanya membuka pintu. Ia lebih membutuhkan banyak energi, lebih dari yang dia punya, saat menemukan manik cokelat itu di depannya. Sangat dekat. Gadis itu berdiri mematung di depan pintunya, tampak terkejut dan terluka sekaligus.
“Kau di sini?” tanyanya dengan suara parau. “Apa yang kau lakukan?”
Dimitri tidak mengatakan apa-apa, ia memang tidak tahu tentang apa yang harus ia katakan. Ia tidak pernah latihan, tidak pernah membayangkan sekalipun bahwa gadis itu akan berdiri di depannya, menatapnya, dan bicara padanya. Semua ini terasa tidak nyata hingga Dimitri tidak bisa menguasai diri.
Sedikit demi sedikit, ia melihat perubahan dari ekspresi gadis itu. Wajah Synne yang tadinya kaku, sekarang menampilkan lebih banyak emosi. Ia menggigiti bibirnya. Dan matanya… Dimitri melihat pelupuk mata gadis itu mulai basah.
“Apa yang kau lakukan di sini, Bodoh? Aku setengah mati mencemaskanmu.” Suaranya juga bergetar hebat, Dimitri mencatat.
“Yeon?”
Pertama kalinya. Ini pertama kalinya ia memanggil nama gadis itu. Shin Yonghwa mengatakan bahwa dia lebih senang dipanggil Yeonni ketimbang Synne, karena semua orang sudah memanggilnya Synne. Dimitri merasakan suaranya aneh, selain karena ia memakai suara Shin Yonghwa, ini juga karena rasanya asing sekali mendengar dirimu sendiri mengucapkan nama gadis yang paling kau khawatirkan di atas planet ini.
“Aku merindukanmu sampai mau gila. Kau kemana saja, huh?!”
“Aku—“
Mendengar gadis itu, gadis yang kau cintai selama ratusan nyaris seribu tahun mengatakan dia merindukanmu, bagaimana menjelaskan rasanya? Ini tidak nyata. Ini tidak terasa nyata.
“Kau melupakanku?!”
Tidak. Sedetik pun tidak pernah. Setiap detik membunuhku karena aku merindukanmu. Seandainya aku adalah makhluk seperti kalian yang dengan mudahnya mati, aku sudah terkubur ratusan tahun lalu.
“Kenapa kau diam saja! Apa aku tampak mengerikan! Apa aku memalukan! Kau… lupa bahwa kau pernah mengatakan kau menyayangiku?! Kau—”
“Tidak.” Dimitri memotong ucapan gadis itu. Ia menjulurkan jari jemarima, mencoba menggapai wajah itu. “Bolehkah… bolehkah aku menyentuhmu?”
Sebelum Synne berkata apa-apa, dengan kaku dan pelan sekali pria itu menyentuhkan telunjuknya di pipi gadis itu, bersama ibujarinya mengusap lelehan airmata Synne. Lalu beralih ke hidungnya, kelopak mata, dan bibirnya. Dimitri memejamkan matanya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini nyata, bahwa ia bisa menyentuh gadis ini. Haruskah mendadak ia berubah menjadi seorang hamba dan berterimakasih kepada Tuhan?
“Hei,” Synne mendadak menepis tangan Yonghwa, membuat mata pria itu membulat karena syok. Gadis itu masih merengut.
“Aku belum memaafkanmu, tahu. Kau luar biasa menyebalkan!” omel Synne seraya masuk, sengaja menyenggol tubuh Yonghwa saat melewatinya, menegaskan bahwa ia benar-benar masih dongkol.
“Aku lapar! Cepat buatkan makanan!”
“A-apa?”
***
Delapan
Hide
“Cobalah bersembunyi. Pepatah mengatakan tidak ada yang bisa menutupi bangkai.”
***
Tidak semua Serdtser memiliki kemampuan istimewa ini. Semuanya mungkin dianugerahi wajah yang rupawan (yang sebenarnya hanya faktor kebetulan di tambah beberapa khasiat sampingan jantung sebagai makanan: jantung membuat awet muda dan mempesona, mitos itu tidak salah), kecepatan yang mengagumkan, dan penglihatan seperti kelelawar yang tajam saat di malah hari, juga pendengaran dan penciuman yang begitu pekanya. Tapi tidak semuanya bisa berubah wujud seenak jidatnya, menjadi siapa saja yang ia inginkan, demi penyamaran iseng maupun untuk keperluan berburu. Satu-satunya yang bisa, yang tertua diantara sejumlah kecil yang ada, adalah Dimitri. Ini tidak didapatkan dengan mudah, tentunya. Ia sudah hidup lebih dari seribu tahun lamanya—kira-kira, ia tidak pernah benar-benar berusaha menghitungnya—sudah membunuh ratusan ribu manusia dan menyantap jantung mereka. Beberapa di antara para korbannya adalah pemburu. Yeah, katanya membunuh seorang pemburu bisa berarti dua hal: jantung mereka bisa menjadi kekuatan, atau… racun. Beruntung, ia mendapat hal pertama, memiliki kekuatan meniru yang menakjubkan dan membuat iri seluruh Serdtser lainnya.
Sekarang, ia sudah menjadi seorang Shin Yonghwa, pria Korea yang tampak baik, kalem, ramah… sempurna. Meski di kenyataan, iblis bersarang di seluruh bagian tidak tampak luar tubuhnya.
Dimitri berjalan ke pintu begitu bel terus berbunyi tidak sabaran. Entah apa yang membuatnya bersedia membuka pintu. Mungkin… sudah saatnya ia untuk keluar. Gadis itu berdiri di sana. Membutuhkan banyak energi ekstra, lebih dari yang dia punya, saat menemukan manik cokelat itu di depannya. Sangat dekat. Gadis itu berdiri mematung di depan pintunya, tampak terkejut dan terluka sekaligus.
“Kau di sini?” tanyanya dengan suara parau. “Apa yang kau lakukan?”
Dimitri tidak mengatakan apa-apa, ia memang tidak tahu tentang apa yang harus ia katakan. Ia tidak pernah latihan, tidak pernah membayangkan sekalipun bahwa gadis itu akan berdiri di depannya, menatapnya, dan bicara padanya. Semua ini terasa tidak nyata hingga Dimitri tidak bisa menguasai diri.
Sedikit demi sedikit, ia melihat perubahan dari ekspresi gadis itu. Wajah Synne yang tadinya kaku, sekarang menampilkan lebih banyak emosi. Ia menggigiti bibirnya. Dan matanya… Dimitri melihat pelupuk mata gadis itu mulai basah. Sesuatu yang sering ia lihat namun jarang sekali ia perhatikan, mungkin ini adalah yang pertama setelah Katya. Dimitri tidak pernah mengerti kenapa manusia mengeluarkan air di matanya saat mereka kehilangan daya dan harapan.
“Apa yang kau lakukan di sini, Bodoh? Aku setengah mati mencemaskanmu.” Suaranya juga bergetar hebat, Dimitri mencatat.
“Yeon?”
Pertama kalinya. Ini pertama kalinya ia memanggil nama gadis itu. Shin Yonghwa mengatakan bahwa dia lebih senang dipanggil Yeonni ketimbang Synne, karena semua orang sudah memanggilnya Synne. Dimitri merasakan suaranya aneh, selain karena ia memakai suara Shin Yonghwa, ini juga karena rasanya asing sekali mendengar dirimu sendiri mengucapkan nama gadis yang paling kau hargai nyawanya di atas planet ini.
“Aku merindukanmu sampai mau gila. Kau kemana saja, huh?!”
“Aku—“
Mendengar gadis itu, gadis yang kau cintai selama ratusan nyaris seribu tahun mengatakan dia merindukanmu, bagaimana menjelaskan rasanya? Ini tidak nyata. Ini tidak terasa nyata.
“Kau melupakanku?!”
Tidak. Sedetik pun tidak pernah. Setiap detik membunuhku karena aku merindukanmu. Seandainya aku adalah makhluk seperti kalian yang dengan mudahnya mati, aku sudah terkubur ratusan tahun lalu.
“Kenapa kau diam saja! Apa aku tampak mengerikan! Apa aku memalukan!” Synne kacau. Dengan mata yang sembab dan pipi dipenuhi bekas air mata dan rambut-rambut menempel di sana, tidak akan salah jika ia disebut mengerikan “Kau… lupa bahwa kau pernah mengatakan kau menyayangiku?! Kau—”
“Tidak.” Dimitri memotong ucapan gadis itu. Ia menjulurkan jari jemarima, mencoba menggapai wajah itu. “Bolehkah… bolehkah aku menyentuhmu?”
Sebelum Synne berkata apa-apa, dengan kaku dan pelan sekali pria itu menyentuhkan telunjuknya di pipi gadis itu, bersama ibujarinya mengusap lelehan airmata Synne. Lalu beralih ke hidungnya, kelopak mata, dan bibirnya. Dimitri memejamkan matanya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini nyata, bahwa ia bisa menyentuh gadis ini. Haruskah mendadak ia berubah menjadi seorang hamba dan berterimakasih kepada Tuhan?
“Hei,” Synne mendadak menepis tangan Yonghwa, membuat mata pria itu membulat karena syok. Gadis itu masih merengut.
“Aku belum memaafkanmu, tahu. Kau luar biasa menyebalkan!” omel Synne seraya masuk, sengaja menyenggol tubuh Yonghwa saat melewatinya, menegaskan bahwa ia benar-benar masih dongkol.
“Aku lapar! Cepat buatkan makanan!”
“A-apa?”
***
“Kau tidak sedang mencandaiku, kan? Ini benar-benar tidak lucu.”
Dimitri—atau mungkin ia harus membiasakan diri dengan identitas barunya, Yonghwa—melihat Synne merengut dan menjauhkan piring telur mata sapi yang semenit lalu dihidangkan Yonghwa dari hadapannya. Pasalnya, pria itu bukan hanya memasak isi telurnya saja, namun ia mencampurnya bersama-sama kulitnya. Yang benar saja!
“Begini aku juga bisa membuat yang jauh lebih baik. Aku benar-benar kelaparan, jadi berhentilah iseng.”
Lalu gadis itu bangkit, meraih apron dari gantungannya dan memakainya sebelum mulai berkreasi dengan omeletnya. Gadis itu memakan waktu setengah jam sebelum berhasil menyajikannya dengan tambahan irisan tomat dan daun seledri kering yang ia temukan di kulkas.
“Sudah berapa hari kau tidak belanja? Isi kulkasmu sampai busuk. Tumben sekali kau membiarkannya.” Tumben-tumbenan pula Synne lebih cerewet dari biasanya. Ia sibuk menata piring dan gelas berisi jus jeruk di atas meja sehingga tidak memperhatikan raut tegang di wajah Yonghwa. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, dan sepertinya Synne pun tidak ingat untuk menagih jawaban. Segera saja, ia duduk di hadapan Yonghwa dan langsung menyantap masakannya sendiri. Lumayan. Sebenarnya ia berbakat jika saja mau rajin, pujinya pada diri sendiri.
Dimitri hanya menatap piringnya untuk waktu lama, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanan manusia… bagi mereka ini adalah barang yang menjijikkan. Sama halnya daging mentah penuh darah bagi manusia, menjijikkan.
“Kau takut keracunan dengan masakanku?” todong Synne.
Saat itu, Dimitri tidak bisa mengatakan atau berbuat apapun selain mulai memotong omeletnya dan memasukkan semuanya ke mulutnya, menahannya sekitar satu jam di tenggorokannya sebelum akhirnya Synne pulang. Saat itulah ia berhasil memuntahkannya. Benar-benar makanan menjijikkan.
Sekarang, Dimitri kembali harus menghela napas lelahnya, setidaknya berpura-pura melakukan itu demi menunjukkan betapa pekerjaan ini merepotkan, menyebalkan, dan mengerikan. Dimitri memegang pisaunya, dan memelototi irisan besar daging sapi merah serta berbagai bahan di depannya.
Barusan salah satu temannya—yang ia tidak bersedia repot-repot mengingat namanya—memintanya membuatkan Fried beef with melted cheese yang kedengarannya seperti menggoreng daging lalu diberi keju dan biarkan meleleh. Namun sepertinya, itu tidak segampang namanya. Dimitri tidak mengerti sama sekali harus diapakan daging setebal dan seberat itu.
“Kau kenapa?” Seseorang menepuk punggungnya, Dimitri menoleh, mendapati tagname Tim pada pegawai ini, orang yang memakai seragam koki yang sama dengannya. “Kau tampak aneh, dan kau membiarkan pengunjung menunggu lama!”
Dimitri tidak menyukai orang ini, ia bicara dengan sok dan gaya membentak. Memangnya siapa yang mau bekerja memasak sesuatu yang menjijikkan demi manusia-manusia sialan itu?
“Bagian ini biar aku saja yang urus,” kata Tim lagi, “kau buat lemonade-nya saja.”
Seharusnya ia bersyukur, kali ini ia bisa lepas. Pekerjaan membuat minuman tidak akan serepot, seaneh, dan sebusuk saat membuat makanan. Dimitri baru saja memperhatikan pegawai lain membuat berbagai minuman, dan ia sudah bisa menghapal semuanya dalam sekali lihat.
Sambil membuat lemonade-nya, Dimitri melirik sesekali pada Tim. Dengan sudut matanya ia memperhatikan bagaimana pria jangkung itu memotong dan mengiris tipis daging sapi merahnya, melumurinya dengan bumbu-bumbu, menata bayam, smoke beef, serta keju mozzarella di dalamnya, menggulungnya, mencelupkannya ke dalam adonan telur, sebelum kemudian menggorengnya. Panas-panas, Tim memarutkan mozarella di atasnya hingga keju itu meleleh dan menabahkan saus BBQ serta daun bayam goreng juga. That’s fried beef with melted cheese. That simple.
Mungkin ia hanya harus menekan dalam-dalam rasa mualnya. Besok-besok ia akan bekerja bersama daging dan sayuran (hal paling menjijikkan dari semuanya selain susu basi yang mereka sebut keju itu), dan ia tidak tahu sampai kapan. Ia hanya harus menjalani kehidupan sebagai seorang Shin Yonghwa. Demi Synne.
This fuckin’ shit stuffs.
***
“Sampai jumpa, Synne sayang!” Serra menyengir lebar di belakang kemudi sambil melambai-lambai penuh kegembiraan pada Synne yang baru saja turun dari mobil dan berdiri tepat di depan flatnya. Bagaimana tidak gembira? Mereka barusaja melakukan kegiatan-kegiatan konyol dan tertawa bersama-sama. Mulai dari berbelanja di Cutty Sark Shoping Center—Serra saja yang berbelanja, sementara Ray dan Synne memasang wajah sebal. “Demi Tuhan, kenapa wanita identik dengan belanja? Kenapa mereka rela menyakiti kaki demi belanja?!” gumam Synne, tidak sadar bahwa dirinya sendiri adalah bagian dari kaum wanita yang barusan ia caci maki. Mereka melanjutkannya dengan menonton film thriller terbaru di Odeon Cinema, yang berujung pada nyaris diusirnya mereka akibat tertawa terpingkal-pingkal demi menghujat adegan yang bagi mereka tidak ada ngeri-ngerinya, malah lucu, sehingga mereka harus berhadapan pada wajah keamanan yang kali ini benar-benar horror. Terakhir, mereka menghabiskan waktu di The Slug and Lettuce, sebuah chain pub bergaya minimalis yang menyajikan menu British. Synne tidak minum, dan ia tidak begitu menyukai tempat terakhir itu, Ray mabuk parah setelah bergelas-gelas cocktail yang ia tenggak, dan Serra masih cukup sadar sehingga masih bisa mengemudi.
Ray, yang tadi menghabiskan dua botol whiskey seorang diri sekarang menyengir lebih lebar dengan mata kurang fokus pada Synne.
“Bye-bye, My Synne! Semoga besok kau lebih berisi—“
“Sialan!” geram Synne seraya memukul kepala Ray yang menyembul dari jendela dengan tasnya.
“Aku masuk dulu. Dan kau,” Synne menoleh pada Ray, “hiduplah untuk besok juga.Kenapa kau gampang mabuk dan selalu ingin mabuk jika membicarakan Sadako versi asli itu?!” Lalu beralih pada Serra. “Sampai nanti, ya! Bye!”
“Bye!”
Dengan itu VW Beetle milik Serra segera meluncur membelah jalanan West ParkSide yang sunyi, nyaris bersamaan dengan Synne yang berbalik dan melangkah menuju bangunan Da Vinci Lodge.
Hari ini sangat melelahkan. Seharian ia bersenang-senang bersama dua orang gila yang mengaku sahabatnya itu. Lelah baru benar-benar terasa menggerogoti setelah ia berhenti tertawa dan ditinggal sendirian seperti sekarang. Ia rindu kasur, demi Tuhan! Synne sudah merencanakan akan tidur tanpa gangguan sampai jam sepuluh besok, bahkan. Dan baru disadarinya juga, ada seseorang yang dirindukannya.
Gadis itu mengecek ponselnya selama perjalanan menuju flatnya yang hanya di lantai dua. Wajahnya yang kusam masih agak lebih cerah saat memeriksa jumlah panggilan atau pesan, dan berubah menjadi titik redup terendah saat tidak menemukan apapun. Tidak ada panggilan atau setidaknya pesan dari Yonghwa! Oh, astaga! Apa yang sedang pria keparat itu lakukan, memangnya?! Berkencan dengan wanita lain?!
Dia mungkin sibuk. Yeah, Synne tahu. Tapi bahkan tidak ada secuil pun pesan?! Tidak ada sama sekali?! Padahal sewaktu usai berbelanja tadi Synne sempat mengirimi pesan, menanyakan dengan sepenuh penekanan harga diri tentang apa yang sedang pria itu lakukan. Itupun tidak mendapat balasan! Keterlaluan! Synne merasakan napasnya memburu. Ia tidak habis pikir kenapa pria itu mengabaikannya! Rasanya seperti dilukai. Harga dirinya terluka. Synne merasa sakit kepala memikirkan semua kemungkinan sehingga tidak ingin memikirkannya lagi. Tahu-tahu ia sudah berdiri di depan pintu flatnya. Saat itu ia sudah memutuskan untuk tanpa diganggu siapapun atau apapun kembali ke pelukan cinta pertamanya: kasur. Sehingga tanpa menyalakan lampu, dan hanya dengan melemparkan bootnya ke sembarang arah, Synne sudah berjalan terhuyung-hyung untuk seketika terbaring di kasur.
Namun bayangannya tentang kasur yang empuk dan nyaman salah besar. Ia menemukan cinta pertamanya dan cinta abadinya itu telah berubah bentuk menjadi tonjolan keras yang bergerak, dan bisa terteriak. Seketika Synne menjerit sambil berlari mencari saklar lampu.
Detik berikutnya, kamar itu seketika terang benderang. Synne menemukan seseorang duduk di kasurnya. Seseorang yang baru bangun tidur. Seorang pria, dan ia tidak terlalu menyukai pria ini.
“Demi Tuhan, Mark! Apa yang kau lakukan di sini?!”
Pria itu Mark. Jelasnya, Marcus William Choi. Oh, bukan, nama aslinya Choi Ki Hyun, nama yang diberikan sang ibu yang mencintai ketradisionalan saat pertama kali dirinya di lahirkan di dunia ini. Hanya saja, ayah mereka, Choi Hwang Min yang kebarat-baratan itu, dan seorang CEO yang memiliki perusahaan cukup besar yang berkembang lebih pesat di Eropa itu, lebih senang memanggil anak-anaknya dengan nama barat Mark dan Synne. Ya, Mark adalah kakak Synne, orang yang Synne sebut sebagai terdakwa atas pencurian keberuntungan di dalam perut ibu mereka.
Mark adalah orang populer di Korea Selatan, sebagai salah seorang personel paling mempesona dari salah satu boyband paling bersinar di dunia. Pria ini memiliki jadwal menggunung, harus pergi kemana-mana dalam waktu yang kalau bisa menjadi dua puluh lima jam sehari dan delapan atau smebilan hari seminggu. Jadi agak sulit dipercaya bagi Synne saat pria itu tiba-tiba muncul di flatnya, menyengir aneh dan tampak kumal. Seharusnya Synne memfoto kakaknya yang sialan itu saat ini juga dan mempostingnya di instagram, atau menjualnya pada papparazzi, dengan begitu seperti membunuh dua nyamuk dalam sekali tepuk; ia akan mendapat uang, dan Mark akan ditinggalkan penggemarnya. Ah, menyenangkan sekali andai itu terjadi! Pikir Synne. Sayangnya, ia sedang terlalu lelah bahkan untuk sekedar mengetahui dimana tadi ia menjatuhkan ponselnya.
“Hai, adikku yang manis! Kau sudah mandi? Kau kucel sekali.”
Synne hanya merengut. Ia terlalu lelah untuk meladeni titisan setan yang satu itu. Dan Synne tidak memiliki rencana untuk melupakan keinginannya tidur hanya demi si tidak-penting-Mark. Apapun tidak boleh menghalangi Synne agar bisa istirahat.
“Minggir, aku mau tidur!” Dengan kakinya yang terbilang kurus lagi kurang panjang, Synne menyepak-nyepak punggung Mark agar segera menyingkir dari kasur tercintanya, seolah Mark itu adalah tungau atau sebangsanya.
Tapi, bukan Mark namanya, dan bukan titisan iblis julukannya jika ia mengalah begitu saja. Mark mempertahankan tubuhnya tetap berada di kasur sementara tangannya yang kekar menangkap kaki Synne dan menggulingkan gadis itu jauh-jauh.
“Aku baru tidur dua jam. Aku mengantuk sekali.”
“Ini kasurku! Choi Ki Hyun!” teriak Synne
“Kau masih punya sofa, Choi Yeon Hee!” Mark balas berteriak, dan dengan itu ia berhasil menggulingkan Synne yang memang selalu tidak berdaya sebelum kemudian menggelng diri dengan selimut dan memasang seringai kemenangan yang seribu kali lipat menyebalkan.
“Kau tidur di lantai saja!”
“Ayo bangun dari kasurku!”
“Ini kasurku, Choi Ki Hyun!”
Synne berteriak dan Mark menutupi telinganya dengan bantal. Synne bangkit, meski tenaganya tidak seberapa, tapi ia bukan seorang Synne jika tidak melawan. Ia melakukan apa saja, menarik Mark, mendorongnya, menggelitiknya, sampai menarik selimutnya. Keadaan berantakan sekali ketika Synne menghentikan segala perlawanannya dengan hampir putus asa.
“Yak! Kau itu kan laki-laki dan kau lebih tua dariku! Kenapa kau kekanak-kanakkan sekali!!!”
“Terserah saja. Aku tidak akan kemana-mana!” Mark melongok sebentar, memeletkan lidahnya dan kembali tenggelam dalam balutan selimut yang luar biasa menggoda Synne. Malam di luar sana tadi begitu dingin sehingga tidak ada yang tampak lebih baik selain selimut, mandi air hangat pun tidak.
Jika ini merupakan sebuah film, maka ini adalah film angst yang berakhir tragis. Synne jatuh kelelahan dan bersandar di tepian kasur setelah usahanya yang percuma demi mengusir Mark. Mark itu seperti wabah penyakit yang sulit diberantas.
Dengan kesal, gadis itu mengambil tasnya yang sudah terlempar ke depan pintu dan memakai kembali mantelnya.
“Kalau begitu aku akan menginap di flat Yonghwa Oppa saja!”
“APA?!” Seketika Mark bangun dari (pura-pura) tidurnya.
“Aku mau menginap di tempat Yonghwa Oppa. Kenapa?!”
Synne belum sempat kabur—dan sebenarnya ia tidak terlalu ingin pergi kalau bukan karena terpaksa, cuaca di luar menakutkan—karena tahu-tahu saja Mark sudah buru-buru mengejarnya dan mencengkeram pergelangan tangannya.
“Hei, kau itu anak perempuan! Kenapa mau menginap di tempat laki-laki?!” omel Mark seraya menjentik ubun-ubun Synne hingga gadis itu meringis.
“Kau sendiri mengenalnya dengan baik. Dia orang baik. Jauuuh sekali lebih baik darimu! Dia tidak akan macam-macam denganku.”
“Memangnya ada pria waras yang berminat macam-macam denganmu?”
Synne melotot, namun belum sempat bereaksi apa-apa saat Mark melanjutkan ucapannya. “Tapi laki-laki dimana-mana sama saja. Mereka itu berbahaya.” Mark mengucapkannya dengan penuh ancaman, Synne mulai membayangkan ada semacam backsound menakutkan tadi.
“Kau lupa kau juga laki-laki, Mark?”
“Panggil aku Oppa. Kau itu tidak ada sopan-sopannya. Dan ya, karena aku laki-laki maka aku tahu laki-laki itu seperti apa.”
Synne merengut kesal, namun ia menjatuhkan kembali tasnya dan melepaskan mantelnya. “Kalau begitu aku akan tidur di kasur dan kau tidak boleh mengganggu! Kalau bisa kau saja yang menginap di flatnya!”
Mark diam saja ketika Synne merayap ke kasurnya dan tidak berapa lama, sepertinya ia sudah tertidur kelelahan. Mark duduk di sofa, menyalakan tivi, namun matanya tidak fokus ke sana.
Beberapa jam lalu, ia sudah bertemu Shin Yonghwa. Dan Mark tidak tahu kenapa ia tidak menceritakannya pada adiknya.
[flashback]
“Kau kabur kemana sebenarnya, Mark?” suara Manager di ujung telpon kedengaran khawatir. Jelas, mereka sedang di London untuk tur, bukannya Korea. Bagaimana mungkin anak itu berkeliaran sendiri di jalanan kota London bahkan tanpa izinnya? Bagaimana kalau tersesat atau dikejar-kejar papparazzi? Mark itu benar-benar. Membuat siapapun migrain.
“Maaf, Hyung. Aku harus mengunjungi adikku sebentar,” balas Mark dengan nada meminta maaf. Hah, kalau bukan karena ibunya yang memaksa dan menceramahinya habis-habisan selama dua jam penuh, Mark tidak akan mau repot-repot memeriksa apakah adiknya, Synne, sekedar masih hidup atau tidak. Oke, sebenarnya ia tidak sekejam itu juga, dan jauh di lubuk hatinya sebenarnya ia pernah khawatir juga waktu Synne mengalami kecelakaan beberapa tahun silam, atau saat gadis itu terlambat pulang dari sekolah karena salah naik bus. Ia peduli, sayangnya hanya pada saat-saat tertentu yang langka terjadi. Seringnya mereka hanya menghabiskan kebersamaan dengan saling mengejek, mengutuk, dan mendoakan semoga salah satu dari mereka adalah anak yang tertukar.
“Oh? Benar juga. Adikmu di London, ya. Kalau begitu baiklah, tapi pastikan kau kembali sebelum jam sembilan, kita ada interview.”
“Tentu, Hyung. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku janji!”
“Janjimu itu banyak yang palsu, Mark. Tapi yasudahlah. Pokoknya kau tidak boleh terlambat! Kalau tidak—“
“Bye, Hyung!” ujar Mark buru-buru, sambil mennyengir tidak tahu diri ia menutup ponsel dan menyimpannya di dalam saku. Telinganya masih trauma setelah dimarahi sang ibu, sekarang ia tidak bisa menerima omelan lebih-lebih lagi.
Dengan susah payah, ia berhasil menemukan flat anak cecurut itu yang berada di jalan…. Niat awal Mark mulanya hanya ingin memastikan adiknya satu-satunya itu masih bernapas atau tidak saja, yang kemudian bertambah keinginan untuk menumpang pemakaian kasur barang satu dua jam karena selama di pesawat Mark tidak bisa beristirahat dengan tenang. Beruntung, waktu itu ada seorang kakek keluar dair flat sehingga Mark hanya perlu menyelinap dan mencari kamar Synne tanpa harus menunggu di depan flat seperti anjing tersesat dulu. Ketika sampai di depan kamar gadis itupun, ia menemukannya tak terkunci.
Mark mendorong pintu itu pelan, dalam hati ia sudah mempersiapkan suaranya agar nanti sekeras mungkin saat mengagetkan si kecil Synne. Namun kemudian, dirinya sendirilah yang dibuat kaget.
Mark menemukan Yonghwa, tapi bukan hanya itu masalahnya. Shin Yonghwa berada di flat Synne. Hal itu tidak lagi terasa janggal sejak hari dimana Yonghwa datang ke kediaman orang tua mereka dan meminta secara langsung agar diizinkan melamar Synne. Ya, Synne yang masih balita itu! membuat Mark ingin tertawa berguling-guling mendengarnya sampai bercucuran air mata. Tapi berkat kesungguhan pria itu, orang tua Mark dan Synne pun setuju. Wajar saja seorang tunangan bermain ke flat calon istrinya. Yang aneh adalah, sesuatu yang sedang di lakukan Yonghwa.
Mark menemukan pria itu di ambang dapur, sedang memunggunginya. Ia berdiri dan tampak seolah sedang memakan sesuatu dengan lahap—terdengar kunyahan dan geraman senang. Tapi apa yang sedang dimakannya dengan berdiri dan tidak sabaran?
“Yonghwa ssi.”
Yonghwa menoleh. Sesaat, sesaat yang terasa seperti ilusi, Mark melihat darah berlumur di mulut pria itu, begitu juga dengan sesuatu yang seperti gumpalan merah di genggaman tangannya. Mark mengedipkan mata, apa yang salah dengan penglihatannya?! Ia melihat Yonghwa terburu-buru pergi ke wastafel dan membersihkan apapun itu yang ada di mulut dan tangannya. Dan setengah tidak percaya akan penglihatannya, Mark melihat air yang mengalir dari wastafel berubah merah sebelum memasuki pembuangan.
“Oh—“ Yonghwa menoleh secepatnya, menghampiri Mark, dan tidak mengatakan apa-apa lagi selain ‘Oh’ yang barangkali berarti halo.
Dimitri hanya tidak bisa memutuskan apakah ia mengenal orang ini atau tidak. Apakah ia harus pura-pura bersikap ramah atau tidak. Astaga, penyamaran ini menjemukan, dan lebih menyiksa dari sebelum-sebelumnya. Biasanya ia tidak akan peduli. Ia hanya akan meminjam wajah dan identitas tanpa repot-repot memikirkan apakah sikapnya berubah dan bagaimana orang di sekitar bereaksi terhadapnya. Tapi kali ini… entah bagaimana ada semacam perasaan bersalah yang tidak mau pergi, menempel ketat dan begitu lengket di pikirannya.
Sementara Mark memandanginya dengan kening berkerut yang hampir-hampir tdiak berusaha ia sembunyikan. Demi Neptunus! Ia sudah datang jauh-jauh dari Korea. Mungkin berlebihan untuk mengharapkan sebuah pelukan dan ciuman—dan Mark juga sama sekali tidak mengharap itu—tapi hanya satu kata ‘Oh’ yang tidak ada hangat-hangatnya sama sekali membuatnya keheranan. Biasanya Yonghwa akan selalu menyapanya lebih dulu jika bertemu, dan dengan cara yang sangat sopan. Tapi kali ini, tatapan pria itu bahkan seolah Mark adalah maling yang ketahuan memasuki rumahnya.
“Apa si pemalas ada di flat? Mom memaksaku untuk memeriksanya.”
“Pemalas?” tanya Yonghwa kaku. Oh astaga, Mark tahu Yonghwa itu memang orang yang agak serius dan sopan, tapi memangnya ia tidak memiliki secuil pun selera humor? Kasihan sekali.
“Synne, maksudku.”
“Oh, ya. Dia sedang pergi, sepertinya—Ah, dan kurasa aku harus pergi juga.”
Dengan itu Mark tidak lama bersama Yonghwa, pria yang sekarang menurutnya begitu aneh itu. Yonghwa cepat-cepat berpamitan—tidak, Mark lupa bahkan pria itu tidak pamit melainkan hanya pergi begitu saja.
Aneh. Sangat. Apa memangnya yang pria itu telan sebagai sarapan tadi pagi? Omong-omong soal makan… lalu apa yang dilakukannya di ambang dapur tadi itu? Apa… yang sedang dimakannya?
TBC